|
|
|
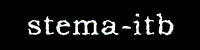 |
|
|
LATAR BELAKANG Perubahan kekuasaan politik di Indonesia tahun yang lalu memberikan iklim baru bagi perkembangan demokrasi di Indonesia dan harus memberikan pondasi yang kokoh untuk tahap-tahap dialektis demokrasi selanjutnya. Akan tetapi, sangat berbahaya bila pergantian kekuasaan politik di Indonesia hanya dikuasai beberapa elit politik dalam sebuah iklim feodalisme warisan kekuasaan lampau yang menghegemoni kepala masyarakat Indonesia, sehingga sudah selayaknya demokrasi dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan bagian dari tugas manusia-manusia pelaku sejarah untuk turut berpartisipasi melakukan koreksi total dan mengubah budaya feodalistik Indonesia (Jawa) menjadi budaya demokratis yang bebas dari feodalisme beserta mitos-mitosnya. Seni yang diabdikan kepada masyarakat adalah alat untuk mendobrak budaya lama yang aus dan mengganti dengan budaya baru dengan konsep yang mengedepankan rasionalitas dan keilmiahan. Bukan dalam arti menolak bentuk-bentuk budaya lama, akan tetapi menata ulang dalam sebuah bentuk baru sebagai hasil proses analisa budaya yang rasional dan ilmiah. Sastra dan Teater sebagai bagian dari seni tidak dapat dipisahkan dalam fungsinya dalam perombakan budaya, dan mematerialkan tugas-tugas suci seni dalam bentuk-bentuk yang dapat dimengerti oleh masyarakat luas. Hal-hal yang telah ditulis di atas inilah yang memberikan kesadaran bagi kami, Studi Teater Mahasiswa ITB, untuk turut mengambil bagian dalam proses dialektika sejarah masyarakat Indonesia. DASAR PEMIKIRAN Pementasan naskah Mangir karya Pramudya Ananta Toer bagi Studi Teater Mahasiswa (STEMA) ITB menjadi langkah awal bagaimana kita berusaha menuturkan kembali sejarah bangsa ini di masa lalu tidak dalam belenggu mitos-mitos feodalisme tentang kesaktian raja-taja, adil dan bijaksananya penguasa-penguasa feodalis Jawa, dll. Akan tetapi dalam konflik-konflik nyata yang mewarnai perubahan kekuasaan, intrik politik dan semunya sebuah kejayaan feodalisme. Mangir, yang bercerita tentang seputar kekuasaan Mataram, ditulis oleh Pramoedya dalam bahasa yang berbeda sama sekali dengan bahasa yang digunakan penguasa feodalis lampau hingga sejarah versi era Soeharto. Hal inilah yang menjadikannya sebagai sebuah produk sastra yang istimewa untuk disajikan di depan khalayak banyak, bahkan hingga ke desa-desa, karena sebagaimana pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya : alat-alat seni yang sama masih harus digunakan untuk menuntaskan misi budaya baru untuk masyarakat. Studi Teater Mahasiswa (STEMA) ITB berniat mengambil posisi ini dengan mencoba mementaskan naskah Mangir di depan khalayak umum, meskipun baru dimulai di kota-kota besar dimana sebagian besar penikmatnya adalah kalangan terdidik. Dan dari sini, kami beranjak untuk mengolah kembali naskah tersebut sebagai evaluasi atas pementasan kami yang sungguh-sungguh meskipun sangat sederhana. TUJUAN DAN SASARAN Pementasan Naskah Mangir ini ditujukan untuk :
"MANGIR" Pramoedya Ananta Toer Versus "MANGIR" Jawa: Mana yang Lebih Kuat?
Goenawan Mohammad pernah berkata, "Kreativitas Pramoedya adalah kreativitas Polemik." Bahwa segala (sastra) yang keluar dari pena Pram, nampaknya, adalah polemik bagi sastrawan dan budayawan kita. Bagaimana tidak?
Banyak pendapat yang mengatakan, keberhasilan Pram adalah ketika ia mengeluarkan Tetralogi Bumi Manusia -terdiri dari Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca- karena peristiwa besar yang diangkat sebagai setting novel tersebut, tentu saja dengan pertimbangan unsur intrinsik lain. Dari Tetralogi Bumi Manusia terlihat jelas usaha Pram untuk mencoba memberikan pandangan-pandangan penting yang nampaknya luput dari pengamatan sejarah resmi bangsa kita. Saya sendiri melihat sedikitnya ada dua permasalahan utama. Pertama, sejarah keterbentukan Nasionalisme pada awal Kebangkitan Nasional, dan kedua, pengukuhan atas seorang yang bernama Tirto Adhi Soerjo yang digambarkan sebagai tokoh Minke dalam Tetraloginya itu.
Tetralogi Arus Balik sendiri terdiri dari: pertama, Arok Dedes (diterbitkan tahun 1999), naskah kedua masih dalam penelusuran (otomatis belum diterbitkan), ketiga Arus Balik (diterbitkan 1995), dan terakhir: Mangir (rencana diterbitkan 2000).
Maka melalui dua Tetraloginya, Kalau boleh dipersingkat, sebenarnya Pram ingin mencoba gambarkan situasi Nusantara mulai dari munculnya kudeta Arok-Dedes tahun 1222 sampai dengan maraknya Imperialisme, Kolonialisme, dan Kapitalisme -seiring dengan kejatuhan Raja-raja Jawa- yang kemudian dilanjutkan melalui Tetralogi Bumi Manusia, yang berkisah tahap-tahap awal perkembangan Nasionalisme abad ke-20 sebagai cikal bakal Revolusi 1945.
Sedikit tentang Mangir Sebelum membicarakan Naskah Mangir gubahan Pram, ada baiknya digambarkan terlebih dahulu Babad Mangir menurut versi Jawa. Kisah Babad Mangir adalah salah satu dari sekian banyak peninggalan susastra kebesaran Jawa yang termaktub dalam Babad Tanah Jawi setelah masuknya Islam, yang berceritakan perseteruan antara Perdikan Mangir dan (Kerajaan) Mataram: antara Panembahan Senapati, Raja Mataram, dan Ki Ageng Wanabaya, penguasa Perdikan Mangir. Cerita Babad Mangir hingga saat ini tidak memiliki gambaran utuh. Hal ini dengan mempertimbangkan masa Schrikbewind yang menimpa Jawa setelah Majapahit runtuh (1527) yang membuat Jawa tidak memiliki penguasa tunggal. Karena tak bertuan -pada saat itu- tradisi lisan di Jawa lebih mendominasi selama lebih seratus tahun, hingga hampir tidak ada peninggalan-peninggalan kesenian, mulai dari (tulisan) sastra, arsitektur, maupun musik. Maka tak heran penyebaran Babad Mangir-Mataram ini terjadi sebagai cerita lisan dari mulut ke mulut dan otomatis terbagi-bagi menjadi banyak versi: versi kerajaan dan versi penduduk (desa) dari kedua pihak baik Mangir dan Mataram. Karena kesimpang-siuran atas berbagai versi itulah Pram, nampaknya, mempertanyakan kebenaran cerita lisan Babad Mangir sebagai sesuatu yang patut dan harus dilepaskan dari kiasan-kiasan (sanepa) menyesatkan jikalau diterima bulat-bulat sebagai sebuah dogma. Dalam bahasa yang lebih ringkas: Penelaahan secara ilmiah menjadi mutlak, karena Cerita Lisan tentang Mitos-mitos Jawa bukanlah sesuatu yang suci, yang tidak dapat diutak-atik lagi. Namun, justru karena dipicu oleh Cerita Lisan itulah, maka Naskah Cerita Panggung yang digubah oleh Pramoedya Ananta Toer ini tetap memiliki alur pokok yang sama dengan cerita-cerita lisan yang beredar di masyarakat Jawa. Secara tematik, meskipun ditiupkan dari mulut ke mulut dari versi manapun, cerita Babad Mangir-Mataram tetap memiliki kesamaan kurang lebih sebagai berikut. Ketika Majapahit runtuh (1527) Jawa menjadi daerah yang tiada bertuan dan tidak mengenal satu kekuasaan tunggal. Pada saat yang bersamaan pula Wali Sanga mulai menyebarkan Islam melalui Pesisir Utara dan Portugis telah datang ke Sunda Kelapa. Kekuasaan tak berpusat tersebar praktis di seluruh Jawa, menyebabkan keadaan kacau balau perang yang terus-menerus, untuk berebut menjadi penguasan tunggal, membuat pulau Jawa bermandikan darah. Maka yang muncul di Jawa adalah daerah-daerah kecil (desa) yang berbentuk Perdikan dan menjalankan sistem demokrasi desa, dengan penguasanya yang bergelar Ki Ageng. Adalah Ki Ageng Pamanahan menguasai Mataram dan mendirikan Kota Gede pada 1577. Kemudian Panembahan Senapati, anak Ki Ageng Pamanahan naik menjadi raja Mataram. Saat bersamaan muncul pula sebuah daerah Perdikan Mangir dengan pemimpinnya yang bernama Ki Ageng Mangir Wanabaya. Seperti layaknya daerah-daerah lain di Jawa, pertempuran perebutan kekuasaan pun tidak terelakkan, demikian pula antara Mangir dan Mataram. Hal ini sangat dimungkinkan karena letak Perdikan Mangir dan Mataram yang sangat berdekatan, sekitar + 30 km. Maka persaingan antara dua kekuasaan tersebut menjadi tidak terelakkan lagi, terlebih dengan usaha penggenapan janji Ki Ageng Pamanahan kepada Joko Tingkir untuk menguasai sepenuhnya Mataram.Pada akhirnya Mangir kalah. Dan pada 1581 Ki Ageng Pamanahan berhasil menguasai Mataram (dan sekitarnya). Yang menjadi inti dari cerita lisan ini adalah bahwa peristiwa kemenangan Mataram sangat dipengaruhi oleh peristiwa perkawinan antara Putri Sekar Pembayun, anak dari Panembahan Senapati, dengan Ki Ageng Mangir Wanabaya, sang penguasa Mangir. Bahwa peristiwa perkawinan tersebut hanyalah kedok yang dibuat oleh Mataram dalam rangka menghancurkan kekuasaan Mangir dan daerah-daerah lain yang turut membantu Mangir. Ki Ageng Mangir sendiri mati di tangan Panembahan Senapati sewaktu menghadap bersama Sekar Pembayun. Perbedaan Mendasar: Pandangan Pramoedya atas versi Jawa Naskah Mangir, reproduksi Pram yang lahir sebagai karya terakhir dalam Tetralogi Arus Balik, merupakan bentuk unik dalam proses kreatif Pram. Kalau dalam karya sebelumnya Pram selalu menulis dalam genre Novel dan Cerita pendek, maka pada Babad Mangir-Mataram kali ini Pram menuliskannya dalam bentuk Cerita Panggung teateral. Yang lebih menarik, Naskah ini memiliki perbedaan yang sangat fundamental jikalau dibandingkan dengan cerita (baik lisan maupun tertulis) Mangir yang berbahasa Jawa. Ketika mereproduksi Mangir, saat pengasingan di Buru 1976, Pram dalam pertanggung-jawaban-nya mengkelah: dia-lah yang pertama kali menggubah penulisan cerita lisan Babad Mangir ke dalam bentuk naskah (cerita panggung), dari bentuk tradisional Ketoprak menjadi bentuk teateral panggung Nasional, dari bahasa Jawa diubah ke dalam bahasa Indonesia yang menjadi bahasa resmi negara. Bahwa tataran dasar yang digunakan Pram atas cerita Babad Mangir adalah telaah ilmiah yang mengedepankan demitologisasi, rasionalitas dan materialitas. Sehingga jelas-jelas ia menolak mistifikasi, fetis, dan mitos-mitos cerita Jawa yang terkesan membius para pendengarnya. Adapun dalam pertanggungjawabannya atas naskah Mangir yang ia reproduksi, Pram menulis:
Sehingga dalam lakon Mangir yang direproduksi Pram ini semua tokoh dilucuti dari pakaian dongeng dan ditampilkan sebagai manusia biasa, dan dijauhkan dari tanggapan-tanggapan mistik, fetis, dengan impian, usaha, kegagalan dan kesuksesannya. Sebagai tambahan, Naskah Mangir secara Ketoprak Potitik ternyata pernah dimainkan dalam bahasa Jawa oleh Tjipto Mangoenkoesoemo pada tahun 1920 -mungkin ini yang dimaksud dengan Pram. Perubahan bahasa yang dilakukan Pram, dari Jawa menjadi Indonesia pada cerita Babad Mangir-Mataram ini, bukan hanya sebuah desakralisasi atas Jawa atau pun sebuah sebuah translasi biasa antar bahasa, melainkan menjadi sebuah bukti paling radikal atas penolakan Pram kepada "Kebudayaan Jawa" yang dianggapnya telah melakukan proses penipuan selama beratus-ratus tahun tanpa pernah berani diperdebatkan oleh segenap pelaku budaya -khususnya Jawa. Dan yang dilakukan pertama kali adalah: berusaha melepaskan diri dari induk asalnya, Bahasa Jawa. Bahasa di sini, tidak dapat diartikan begitu saja sebagai sebuah ragam ucap atas segala yang muncul dari artikulasi mulut sebagai sebuah semiotika, melainkan sangat jelas -walaupun implisit- pelepasan terhadap sebuah kebudayaan, peradaban feodalisme Jawa, dengan merubah bahasan dari Bahasa Jawa menjadi Indonesia. Dari panggung Ketoprak (tradisional: Bahasa Jawa) menjadi Panggung teateral Nasional (modern: Bahasa Indonesia). Di sinilah letak pentingnya. Ia mengikutsertakan seluruh komponen-komponen bangsa yang menggunakan bahasa Indonesia: Bahwa Jawa bukan sesuatu yang suci, sakral, tanpa kesalahan melainkan justru penuh tipu muslihat dan harus dikoreksi oleh segenap pelaku kebudayaan Modern (Indonesia). Dan ia ingin proses penyadaran itu justru tidak dilakukan melalui Bahasa Jawa. Sebuah penolakan yang luar biasa-sekali lagi, bukan hanya sekedar translasi. Ketika induk semang Bahasa (Jawa) dapat dilepaskan, dan proses "meng-Indonesia-kan" Babad Mangir dapat diterima, maka pembongkaran pun sahih dilakukan. Dengan kebudayaan yang masih baru (Kebudayaan Indonesia), sebenarnya Pram telah bersentuhan dengan alam Modernitas yang mengutamakan metode ilmiah dengan senjatanya: rasio dan logika. Bahwa Naskah Mangir reproduksi Pram ini bukan hanya menjadi sebuah tawaran sejarah (baru) alternatif, melainkan juga merupakan ajakan atas pelurusan sejarah terhadap naskah-naskah lama dan tradisi lisan, yang nampaknya harus ditelaah menurut kondisi paling wajar menurut ukuran manusia biasa tanpa memasukkan sesuatu yang mistis: sebuah proses demitologi. Berikut yang menjadi perbedaan mendasar antara Mangir Versi Pram, dengan Mangir versi "Jawa". Pertama. Pram tidak menerima istilah: kebesaran seorang Penguasa dihubungkan dengan senjata (sakti) yang dimilikinya. Kemajuan sebuah negeri, katakanlah, tidak ditentukan begitu saja, dan diperkecil menjadi sekedar masalah senjata, melainkan faktor manusianya sendiri (taktik perang, kelicikan, kecerdasan dsb). Konsekuensi dari pemikiran pertama di atas, menyebabkan: Pram tidak mengakui kekalahan Mangir disebabkan karena terpotong-potongnya tombak Ki Ageng Mangir (yang konon bernama: Kyai Baru Klinting). Kedua. Setelah melakukan analisa, Pram beranggapan bahwa Kyai Baru Klinting adalah seorang manusia -jadi bukan julukan atas tombak pusaka milik Ki Ageng Mangir- dan benar-benar hidup pada perseteruan Mangir-Mataram. Pada Mitos lama, keberadaan Baru Klinting ditampilkan sebagai seekor ular, kemudian lidahnya saja, yang berubah menjadi tombak sakti di tangan Ki Ageng Mangir Wanabaya. Motif untuk mensandikan apa atau siapa Baru Klinting, menurut Pram, jelas untuk menghilangkan jejaknya dari sejarah, di sorong ke alam dongeng yang tak bakal terjamah oleh usaha pembuktian. Hal ini nampaknya dihembuskan dari pihak kerajaan, baik Mataram maupun Mangir, untuk menjaga kredibilitas Wanabaya, dan Senapati. Penelusuran Pram atas Baru Klinting sebagai seorang manusia dilakukan melalui penelusuran linguistik asal-muasal kata, kemudian berbagai mitos tentang Baru Klinting yang sangat paradoks dan saling bertentangan, juga dari gelar (formasi perang) yang digunakan Mangir, yang disebut Ronggeng Jaya Manggilingan, dan juga dari kemungkinan-kemungkinan yang berlandaskan rasionalisasi atas cerita-cerita sekitar Baru Klinting . Ketiga. Dari prinsip demitologi ini pula, Pram menolak anggapan bahwa Panembahan Senapati adalah anak tidak sah dari Sultan Pajang Hadiwijaya. Selain itu juga, Pram begitu yakin bahwa Baru Klinting adalah anak dari Ki Ageng Mangir terdahulu -sebelum Wanabaya. Wanabaya sendiri, bukan tidak mungkin, menjadi Ki Ageng Mangir II karena proses pemilihan secara demokrasi -karena Mangir tidak berbentuk kerajaan (Monarchy), dan antara kedua-duanya belum pernah didapatkan bukti adanya hubungan darah. Keempat. Proses kematian Ki Ageng Mangir yang dianggap tidak dapat diterima secara logika. Dengan alasannya sendiri, Pram menganggap kematian Ki Ageng Mangir karena kepalanya dipecahkan di Watu Gilang, adalah tidak wajar dan bertendensi, mengandung makna kias (sanepa). Dalam cerita panggung karya Pram ini, kematian Wanabaya digambarkan dengan adegan yang lebih wajar. Kelima. Bentuk dituliskan dalam berbahasa Indonesia yang bergaya Teateral. Berbicara tentang gaya panggung berbahasa Indonesia, maka berbicara pula dengan apa yang disebut Teater Modern Indonesia. Perlu diingat, perkembangan Teater Modern Indonesia pada 1976 tidaklah semaju sekarang. Dalam 24 tahun memungkinkan penafsiran yang sangat bebas atas naskah Pram ini, seiring dengan akselerasi teater kontemporer yang avant-garde. Demikianlah. Mengenai pandangan mana yang benar, mungkin bukan menjadi sesuatu yang patut dijadikan alasan untuk menolak pemikiran Pram. Yang pasti Pram telah memberikan sebuah alternatif lain, dan membiarkan para pembaca/penikmat untuk berpikir, menganalisanya sendiri, dan memilihnya sendiri, tanpa harus dipaksa atau didoktrin, seperti layaknya sejarah yang dituliskan Orde Baru.
|
||||||||||||||||||